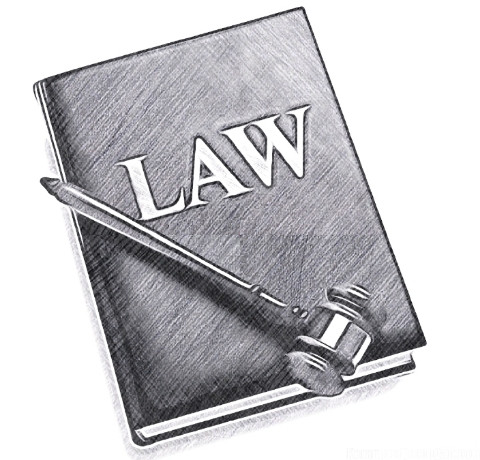Purwakarta, KPonline – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada akhir Oktober 2024 menandai titik balik penting dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
MK memutuskan bahwa 21 norma (pasal/ayat/frasa) dalam klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat. Artinya, pasal-pasal tersebut dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sepanjang tidak dimaknai atau diubah sesuai dengan penjelasan MK.
Lebih jauh, MK meminta pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Keputusan ini muncul sebagai respons dari gugatan yang diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan partai buruh yang menilai bahwa sejumlah norma dalam UU Cipta Kerja melemahkan perlindungan pekerja dan mengandung ketidakpastian hukum.
Berikut ini ringkasan ke-21 norma yang diwajibkan MK untuk diperbaiki atau dimaknai ulang:
1. Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023. Frasa “Pemerintah Pusat” dalam pengaturan penggunaan TKA.
Frasa “Pemerintah Pusat” dinilai terlalu umum dan menimbulkan multitafsir; MK menyatakan inkonstitusional bersyarat kecuali dimaknai sebagai “Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja”. (Kementerian Ketenagakerjaan) harus mengambil peran eksplisit; lebih jelas pengaturan TKA.
2. Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023. “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.”
MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “…dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”. Pengusaha harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia jika kompetensi dan jabatan memungkinkan; pemeriksaan penggunaan TKA diperketat.
3. Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.
MK: norma ini bermasalah karena delegasi aturan terlalu jauh ke perjanjian; harus dimaknai “…tidak melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”. Batas maksimal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi 5 tahun termasuk perpanjangan; perusahaan dan pekerja harus memperhatikan batas ini.
4. Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 Wajib membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan huruf Latin.
MK menyatakan inkonstitusional bersyarat karena norma kurang jelas; harus dimaknai sebagai kewajiban tertulis dalam bahasa tersebut. Pekerja PKWT harus memperoleh perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan huruf Latin; pengusaha tidak bisa mengelak dengan perjanjian lisan/tidak baku.
5. Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023. Ketentuan “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan” untuk alih daya.
Norma dinilai multitafsir; MK menyatakan inkonstitusional bersyarat kecuali dimaknai bahwa “Menteri menetapkan jenis dan bidang pekerjaan alih daya … dalam perjanjian tertulis”. Perlunya regulasi yang jelas mengenai jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan; pekerja outsourcing memperoleh kepastian hak.
6. Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023. Aturan “Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu”.
MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai juga “atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu”. Jadwal kerja dan hari istirahat mingguan harus fleksibel sesuai skema kerja (5 hari atau 6 hari kerja) dan tidak menafikan hak pekerja atas istirahat memadai.
7. Kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023. Kata “dapat” memberi pilihan terkait cuti atau hak lain pekerja.
MK menilai bahwa penggunaan kata “dapat” menimbulkan ketidakpastian — norma harus memberi kepastian, sehingga inkonstitusional bersyarat. Regulasi cuti dan mekanisme hak-hak pekerja harus dirumuskan dengan kata yang memberi kepastian (harus, wajib) bukan sekadar boleh.
8. Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023. “Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat kecuali dimaknai sebagai “penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup wajar bagi pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”. Pemerintah dan pengusaha harus memperhatikan standar penghidupan layak sesuai konstitusi; upah dan jaminan pekerja harus mencerminkan kehidupan layak.
9. Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023. “Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak.”
MK menyatakan inkonstitusional bersyarat kecuali dimaknai sebagai melibatkan dewan pengupahan daerah, termasuk unsur pemerintah daerah, dalam perumusan kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan bukan hanya pemerintah pusat; pemerintah daerah dan dewan pengupahan daerah punya peran penting.
10. Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023. Frasa “struktur dan skala upah” dalam pengupahan.
MK menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “struktur dan skala upah yang proporsional”. Struktur dan skala upah harus dirancang secara proporsional, adil, dan berdasarkan jabatan/kompetensi, bukan hanya formalitas.
11. Pasal 81 angka 28 tentang penyisipan Pasal 88C UU 13/2003. Pengaturan tentang upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Norma ini terkait dengan penghapusan upah minimum sektoral yang sebelumnya ada; MK menilai perlu perlindungan pekerja masa awal. Perusahaan harus mempertimbangkan upah minimum sektoral atau skema khusus bagi pekerja baru (<1 tahun) untuk memastikan keadilan.
12. Pasal 81 angka 28 tentang penyisipan Pasal 88D ayat (2) UU 13/2003. Pengaturan tentang ketentuan upah minimum lainnya (mungkin kriteria lokasi/jenis industri).
MK: norma yang menghapus atau mereduksi upah minimum sektoral dinilai melemahkan perlindungan hak pekerja. Kebijakan upah minimum harus disusun kembali agar mencerminkan kondisi sektoral dan regional, bukan homogen.
13. Pasal 81 angka 28 tentang penyisipan Pasal 88F UU 13/2003. Pengaturan tambahan tentang hak pekerja/buruh atas upah minimum atau kompensasi lainnya.
MK menegaskan bahwa norma pengupahan wajib memberi kejelasan hak pekerja/buruh. Hak pekerja atas upah minimum menjadi fokus kembali; perusahaan harus siap menyesuaikan kebijakan upah.
14. Pasal 81 angka 31 tentang penyisipan Pasal 90A UU 13/2003. Pengaturan baru terkait perlindungan atau hak pekerja/buruh (misalnya hak cuti, istirahat, atau perlakuan adil).
Karena penambahan norma baru, MK menilai perlu kejelasan agar perlindungan pekerja konkret. Pekerja dan serikat pekerja harus memahami pasal-baru ini dan pengusaha menyesuaikan internal policy.
15. Pasal 81 angka 33 tentang perubahan Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003. Perubahan pengaturan outsourcing atau pekerja alih daya (mungkin definisi/ketentuan).
MK menilai bahwa norma outsourcing dalam UU Cipta Kerja membuka ketidakpastian hak pekerja; perubahan ini harus memberi kejelasan. Perusahaan alih daya dan pekerja outsourcing harus memeriksa kembali hak dan statusnya sesuai ketentuan baru.
16. Pasal 81 angka 36 tentang perubahan Pasal 95 ayat (3) UU 13/2003. Perubahan ketentuan mengenai pengalihan atau pergantian hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, atau jenis pekerja.
MK menegaskan perlunya kepastian hak dasar pekerja tak tergantung perubahan skema kerja. Perusahaan dan pekerja harus memantau proses perubahan hubungan kerja agar tidak merugikan pekerja.
17. Pasal 81 angka 39 tentang perubahan Pasal 98 ayat (1) UU 13/2003. Perubahan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kewajiban pemberi kerja.
Norma PHK dalam UU Cipta Kerja semula dianggap melemahkan jaminan pekerja; MK menuntut aturan lebih adil & jelas. PHK harus disertai proses yang jelas dan kompensasi yang pasti; pekerja harus dilindungi dari PHK sewenang-wenang.
18. Pasal 81 angka 40 tentang perubahan Pasal 151 ayat (3) UU 13/2003 Perubahan besaran atau mekanisme uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.
MK menyatakan ketentuan “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut …” sebagai inkonstitusional bersyarat kecuali dimaknai “paling sedikit”. Besaran pesangon minimum harus dipastikan; pekerja punya hak minimal yang tak boleh diabaikan.
19. Pasal 81 angka 40 tentang perubahan Pasal 151 ayat (4) UU 13/2003. Lanjutan perubahan terkait uang pesangon atau penghargaan masa kerja.
Sama seperti poin 18: norma harus memberi kepastian minimum. Perusahaan perlu mengkaji ulang kebijakan pesangon untuk memastikan memenuhi minimum legal.
20. Pasal 81 angka 49 tentang perubahan Pasal 157A ayat (3) UU 13/2003. Perubahan ketentuan yang mungkin berkaitan dengan hak pekerja/lembaga ketenagakerjaan atau denda/sanksi.
Norma yang berkaitan dengan sanksi pidana atau administrasi dihapus atau dilemahkan dalam UU Cipta Kerja; MK menilai perlu kembali diperkuat. Perlindungan terhadap pelanggaran hak pekerja harus dipastikan; regulasi sanksi tak boleh sekadar formalitas.
21. Pasal 81 angka 47 tentang perubahan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003. “Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut…” (merinci bulan-upah berdasarkan masa kerja).
MK menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “paling sedikit”. (Hukumonline) Uang pesangon minimum tidak boleh diabaikan; perusahaan harus memberikan paling sedikit sesuai normatif; pekerja memiliki hak atas pesangon minimum.
Analisis dan Makna Lebih Dalam
Dari daftar di atas dapat dilihat bahwa perubahan yang diminta MK menyentuh beberapa pokok materi utama: penggunaan tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak kerja, alih daya (outsourcing), upah (penghidupan layak, minimum, struktur & skala), istirahat/cuti, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon, serta kejelasan prosedural.
#Beberapa poin penting yang bisa dicermati:
Penggunaan Tenaga Kerja Asing: Norma yang membolehkan TKA “dapat” dipekerjakan tanpa kejelasan pengutamaan tenaga kerja Indonesia dan batasan kompetensi yang ketat dianggap membuka potensi substitusi pekerja lokal, sehingga MK menuntut dimaknai lebih tegas.
PKWT (kontrak kerja sementara): Norma yang membiarkan perjanjian kerja menentukan jangka waktu tanpa batasan jelas menyebabkan potensi “kontrak abadi” bagi pekerja. MK memerintahkan batas maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan.
Outsourcing (alih daya): UU Cipta Kerja memperluas skema alih daya, namun tanpa definisi dan batasan pekerjaan yang jelas, pekerja alih daya berada dalam posisi lemah. MK menghendaki undang-undang yang tegas menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
Upah & Penghidupan Layak: Norma yang menghapus atau mereduksi pengaturan upah minimum sektoral, struktur dan skala upah, serta frasa yang samar (“penghidupan layak bagi kemanusiaan”) dinilai tidak cukup memberikan kepastian hak pekerja. MK menuntut norma yang tegas.
Hari Istirahat & Cuti: Beberapa norma dalam UU Cipta Kerja mengubah atau menghapus ketentuan hari istirahat dan cuti; MK mengembalikan prinsip bahwa pekerja harus memiliki hak istirahat yang memadai (misalnya 1 relasi 6 hari kerja atau 2 relasi 5 hari kerja).
PHK dan Pesangon: Norma yang mereduksi kewajiban pengusaha atau memberi ruang interpretasi luas merugikan pekerja. MK menegaskan bahwa mekanisme PHK dan besaran pesangon minimum harus jelas dan dikembalikan statusnya sebagai hak pekerja.
Kewenangan dan Bahasa Undang-Undang: Beberapa norma menggunakan frasa yang fleksibel (“Pemerintah menetapkan”, “dapat”, “sebagian”) yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. MK menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak pekerja harus diatur dalam Undang-Undang (UU) sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. (DDTCNews)
Secara keseluruhan, MK menilai bahwa regulasi dalam UU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan tersebut tidak cukup memberikan kepastian dan perlindungan hak pekerja seperti yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D (hak atas pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil) dan Pasal 28E (hak untuk membentuk serikat pekerja). Oleh karena itu, norma-norma tersebut harus diperbaiki, dimaknai secara pro-pekerja, atau diganti melalui undang-undang ketenagakerjaan yang baru.
#Implikasi Bagi Pekerja, Serikat Pekerja, dan Pengusaha
•Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja
Putusan MK ini memberi angin segar bagi perlindungan pekerja dan legitimasi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak. Beberapa implikasi praktis:
Pekerja kontrak (PKWT) mulai memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut batas maksimal masa kerja dan perpanjangan.
Pekerja outsourcing bisa menuntut kejelasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan dan hak-hak yang setara.
Upah minimum, struktur dan skala upah, serta hak atas penghidupan layak mendapat landasan baru dalam putusan MK, yang dapat diperjuangkan melalui perundingan sosial dan PHK/negosiasi.
Serikat pekerja bisa menggunakan putusan MK sebagai basis advokasi agar regulasi perusahaan disesuaikan, dan jika perlu mendorong revisi UU Ketenagakerjaan.
•Bagi Pengusaha
Pengusaha harus menyiapkan penyesuaian kebijakan perusahaan agar sesuai dengan ketentuan baru/yang akan datang:
Kebijakan penggunaan TKA perlu ditinjau ulang, memastikan pengutamaan pekerja Indonesia bila kompetensi memungkinkan.
Kontrak PKWT dan perpanjangan harus diperhatikan jangka waktu maksimal dan bentuk perjanjian terulis.
Skema alih daya (outsourcing) harus dievaluasi: jenis pekerjaan, hak pekerja, dan pengawasan.
Struktur upah, relasi jabatan, skala upah, serta kebijakan cuti dan hari istirahat harus disesuaikan agar memenuhi standar “penghidupan layak”.
Prosedur PHK dan kompensasi (pesangon) harus memastikan bahwa pekerja memperoleh hak minimum sebagaimana dimaknai oleh MK.
Kebijakan internal perusahaan harus transparan, tertulis, dan punya kepastian hukum agar tidak terkena risiko litigasi atau sanksi.
Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Putusan MK memberi mandat kepada pemerintah dan DPR untuk:
1. Menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, yang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, dengan waktu paling lama 2 tahun. (DDTCNews)
2. Melibatkan pekerja/buruh, pengusaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil dalam proses legislasi agar norma yang dihasilkan inklusif dan memiliki legitimasi sosial.
3. Memastikan regulasi pelaksana (PP, Perpres, Permen) tidak menggantikan fungsi undang-undang dalam pembatasan hak pekerja, karena MK menyoroti banyak norma yang “digeser” ke PP. (DDTCNews)
4. Memastikan bahwa regulasi baru memperjelas mekanisme dan batasan-batasan penggunaan TKA, outsourcing, PKWT, upah, PHK/pesangon, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau ruang praktik yang merugikan pekerja.
Putusan MK mengenai 21 pasal dalam klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja merupakan momen penting: bukan hanya sebagai koreksi regulasi teknis, tetapi juga sebagai peringatan kuat bahwa hak pekerja, kejelasan kontrak kerja, pengupahan yang adil, dan perlindungan terhadap status pekerja adalah bagian tak terpisahkan dari konstitusi kita. Bila regulasi ketenagakerjaan terus dibiarkan “tidak jelas” atau penuh celah, maka muncul ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan pekerja dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang tidak sehat.
Bagi pekerja dan serikat pekerja, keputusan ini adalah titik pijak untuk memperkuat posisi tawar dan advokasi. Bagi pengusaha, ini adalah sinyal bahwa era keseimbangan antara investasi dan hak pekerja semakin ketat dan memerlukan adaptasi. Bagi pembuat kebijakan, ini adalah tugas besar untuk menyusun undang-undang yang tidak semata mengejar efisiensi investasi, tetapi juga memastikan keadilan kerja, perlindungan pekerja, dan stabilitas sosial.
Seiring proses pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru ke depan, akan sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pengusaha, pekerja, serikat—untuk berpartisipasi aktif dan memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar memberi perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi pekerja dalam praktik sehari-hari.