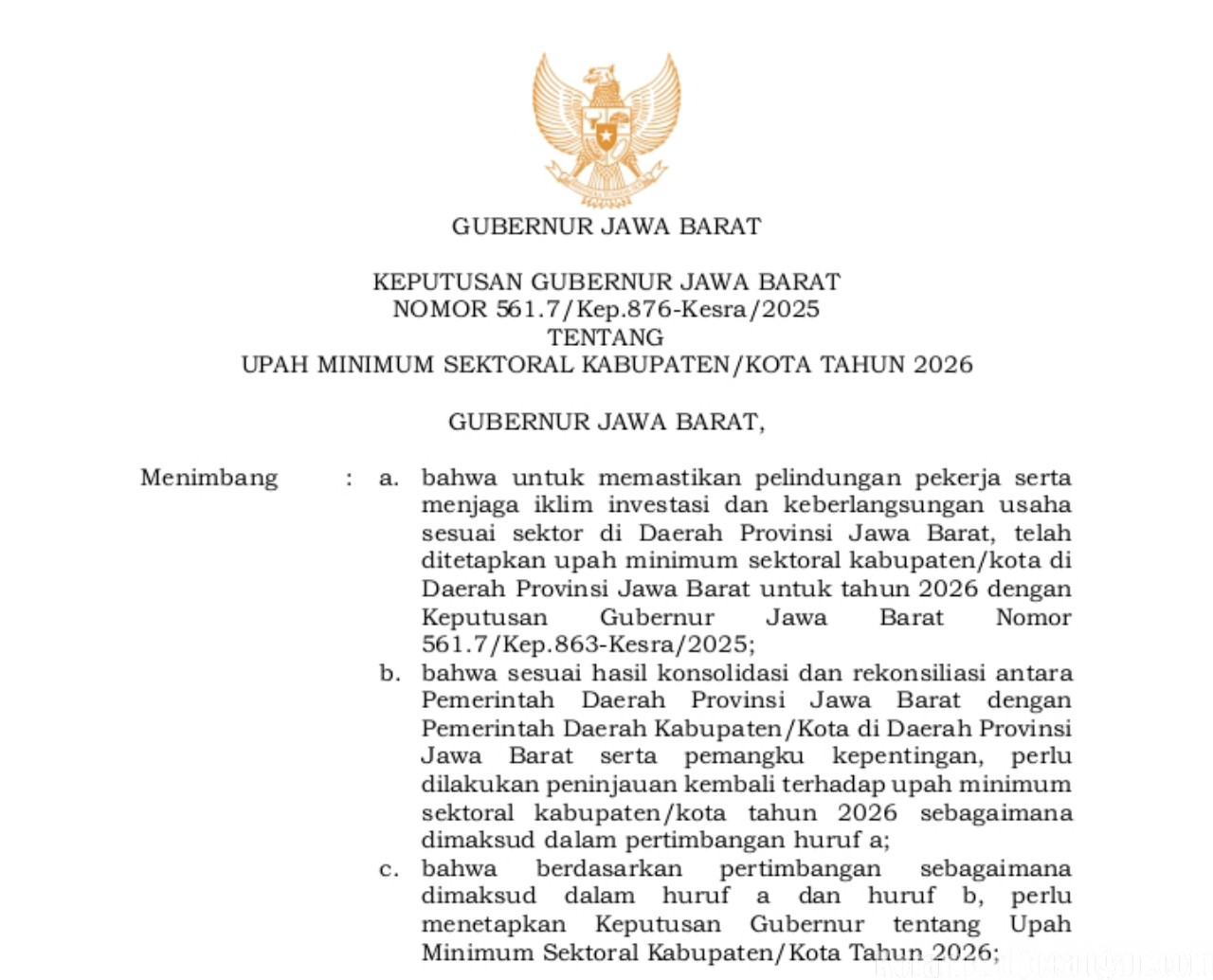Bandung, KPonline-Menurut kaca mata kelas pekerja, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 kian memperlihatkan wajah buram tata kelola pengupahan nasional. Regulasi yang seharusnya berpijak pada norma hukum, data objektif, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), justru dinilai telah direduksi menjadi sekadar asumsi dan opini sepihak penguasa.
Akibatnya, UMSK yang lahir, bukan menjadi instrumen keadilan. Melainkan simbol kegagalan negara melindungi kaum buruh. SK UMSK sejatinya bukan kebijakan opsional. Ia adalah mandat regulatif yang lahir dari kebutuhan riil sektor-sektor industri dengan karakteristik kerja, risiko, dan produktivitas tertentu sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Namun dalam praktik penetapan UMSK 2026 di Jawa Barat, banyak pihak menilai regulasi tersebut diperlakukan seolah hanya tafsir bebas pemerintah daerah, bukan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara konsisten dan berkeadilan.
Publik dan berbagai serikat pekerja menyoroti bahwa penetapan UMSK 2026 di Jawa Barat lebih didasarkan pada asumsi stabilitas investasi ketimbang amanat peraturan perundang-undangan. Pertimbangan ekonomi makro dan kekhawatiran pengusaha dijadikan dalih utama, sementara realitas kebutuhan hidup buruh dan rekomendasi sektoral justru dipinggirkan.
Padahal, dalam mekanisme pengupahan, UMSK memiliki dasar hukum yang jelas. Ia bukan hadiah politik, bukan pula kebijakan sukarela gubernur. Dimana, ketika rekomendasi sektoral dari kabupaten/kota dipangkas secara sepihak, bahkan sebagian besar tidak diakomodasi dalam Surat Keputusan Gubernur, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka upah, melainkan legitimasi regulasi itu sendiri.
“Regulasi diperlakukan seperti opini. Bisa diterima kalau cocok, diabaikan kalau dianggap mengganggu,” ujar seorang pengurus serikat buruh FSPMI di kawasan industri Purwakarta.
Keputusan UMSK 2026 Jawa Barat semakin menuai kritik karena dianggap sebagai anomali nasional. Di sejumlah provinsi lain, UMSK ditetapkan secara lebih komprehensif dan selaras dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Akan tetapi di Jawa Barat, jumlah sektor yang direkomendasikan jauh lebih banyak dibanding yang akhirnya ditetapkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah regulasi pengupahan masih menjadi rujukan, atau sekadar formalitas administratif yang boleh dipilih-pilih?
Ketika satu provinsi dengan kawasan industri terbesar di Indonesia justru memotong substansi UMSK, maka pesan yang sampai ke buruh sangatlah jelas yakni hukum bisa dinegosiasikan, selama buruh yang dikorbankan.
Padahal, harapan buruh sempat menguat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 yang menegaskan pentingnya upah minimum sebagai jaring pengaman hidup layak. Namun dalam polemik UMSK 2026 Jawa Barat, semangat putusan MK itu dinilai tidak tercermin dalam kebijakan daerah.
Diharapkan mampu memperbaiki formula dan memperluas perlindungan sektoral, namun kebijakan UMSK 2026 Jawa Barat justru menyempit. Regulasi yang seharusnya memperkuat posisi buruh wilayah Jabar malah dijadikan alasan untuk membatasi kenaikan upah dengan dalih tidak diwajibkan atau tidak relevan.
Bagi serikat buruh, ini adalah bentuk pengingkaran konstitusional secara halus. Tidak dengan menolak hukum secara terang-terangan, tetapi dengan mengosongkan maknanya.
Singkatnya, polemik ini memperlihatkan pergeseran peran negara dari pelaksana regulasi menjadi penafsir subjektif regulasi. Negara tidak lagi hadir sebagai wasit yang adil, melainkan sebagai pihak yang memilih keberpihakan dengan membungkusnya dalam narasi normatif.
Ketika pejabat publik menyampaikan bahwa UMSK harus disesuaikan kondisi industri tanpa merujuk utuh pada regulasi yang ada, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, melainkan produksi opini kekuasaan.
Tentunya, situasi ini berbahaya. Jika regulasi bisa direduksi menjadi asumsi, maka tidak ada jaminan hukum yang benar-benar pasti. Hari ini UMSK, besok bisa jadi hak normatif lainnya.
Maka, tak mengherankan jika polemik UMSK 2026 Jawa Barat terus memantik gelombang protes hingga saat ini. Aksi unjuk rasa, pengaduan ke Pemerintahan Pusat (Istana Negara), hingga wacana gugatan hukum menjadi pilihan yang terus mengemuka.
Serikat buruh disini menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah menjaga marwah regulasi agar tidak dipermainkan oleh kepentingan jangka pendek. Sebab, jika regulasi hanya dianggap opini, maka buruh tidak punya kepastian masa depan.
Polemik UMSK 2026 Jawa Barat menjadi pelajaran berharga persoalan ketenagakerjaan nasional. Regulasi yang kuat di atas kertas, tetapi rapuh dalam implementasinya. Selama regulasi diperlakukan sebagai asumsi dan bukan perintah hukum, konflik pengupahan pasti akan terus berulang dikemudian hari.